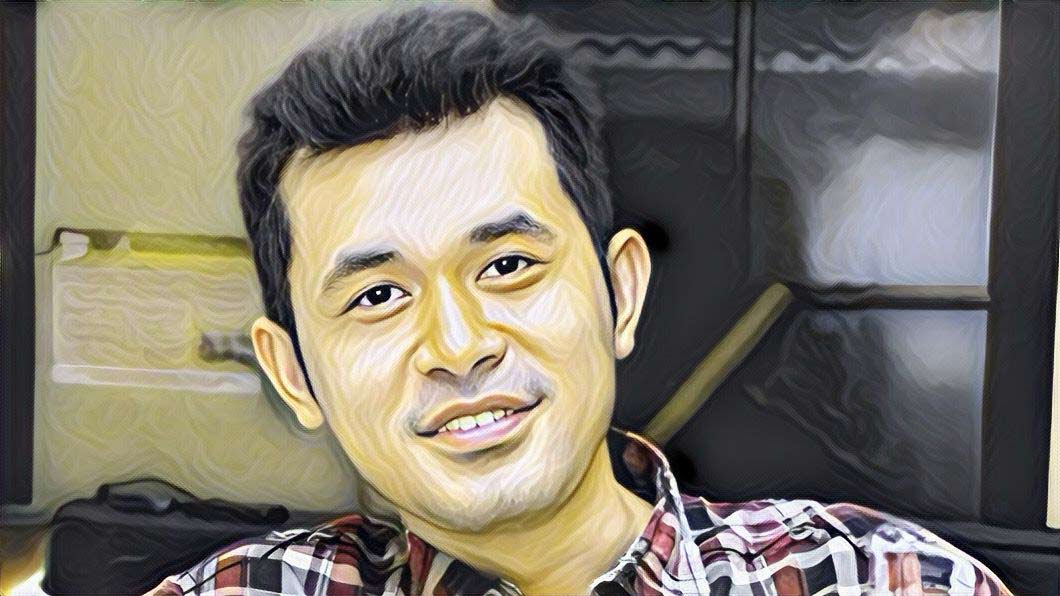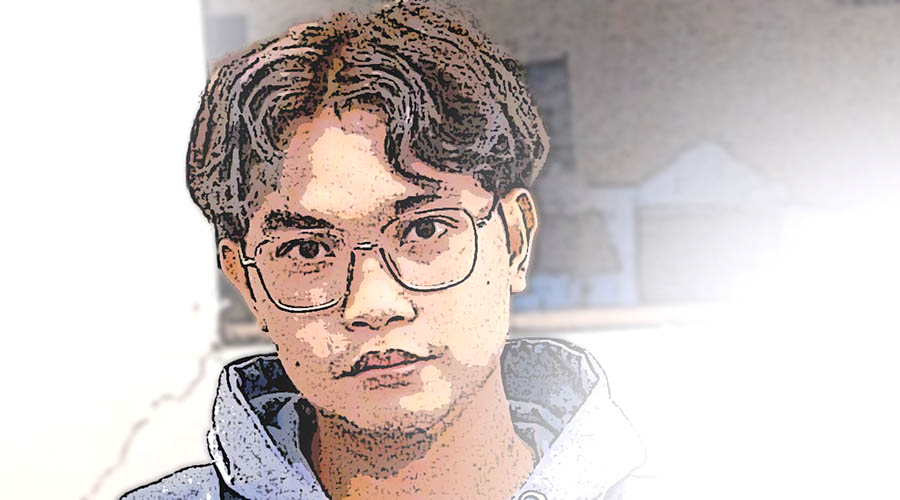MASYARAKAT awam menyoroti demokrasi hanya sebatas memilih pemimpin setiap pemilu lima tahunan sebagai sebuah ritual demokrasi. Begitu juga, sebagian mereka yang terdidik memiliki persepsi yang sama.
Mereka menganggap demokrasi sebagai sistem yang terbaik dari yang terburuk dalam siklus kepemimpinan. Itu jika dibandingkan dengan sistem kerajaan, atau teokrasi. Mereka pun menyakini bahwa bergilirnya kepemimpinan diharapkan akan mewujudkan pemerintahan yang good governance, dan demokratis. Namun, persepsi itu ternyata mitos belaka.
Faktanya, ada pemimpin yang awalnya dipilih secara demokratis, tetapi pada saat mereka menguasai singgasana kekuasaan dalam periode lama, justru malah berubah menjadi seorang diktator.
Sebut saja Hitler, Napoleon Bonarparte, Josep Stalin, Bennito Mussolini, Hugo Chavez, dan masih ada yang lain. Bahkan, kadang mereka mengubah konstitusi untuk tetap bertahan dalam kekuasaan. Dan, mereka pun mencoba untuk membungkam lawan politik atau mereka yang menjadi oposisi. Berubahlah seketika itu negara menjadi anti demokrasi.
Demokrasi ternyata juga dapat menjadi sarana munculnya dinasti politik. Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dengan hubungan keluarga.
Menurut Ari Dwipayana, politik semacam itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya telah lama berakar secara tradisional. Jika itu telah terjadi, maka selamat datang era otoriterianisme.
Berdasarkan sebuah buku karya Juan Linz, bertajuk The Breakdown of Democratic Regimes yang terbit tahun 1978, ia menyoroti perilaku politikus yang bisa memperkuat atau mengancam demokrasi.
Masyarakat sebaiknya khawatir, dan waspada jika seorang politikus sudah menunjukkan indikator kunci berikut ini.
Pertama, apabila politikus menolak aturan main demokrasi, dengan kata-kata ataupun perbuatan, kedua menyangkal legitimasi lawan. Ketiga, menoleransi atau menyerukan kekerasan, atau keempat, menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil, termasuk media massa.
Bahkan Linz memperkuat pendapatnya dengan mengatakan politikus yang memenuhi satu syarat saja sudah menunjukkan simtom yang mengkhawatirkan publik.
Anehnya lagi, jika terjadi momen penggantian penguasa dengan pemilu, justru orang-orang terdidik dan intelektual itu malah alergi membincangkannya, dan berperilaku paradoks. Contohnya di group-group WhatsApp. Mereka selalu ngomong bahwa groupnya bukan untuk bicara politik, group ini untuk informasi dan obrolan hal-hal yang terkait akademis dan ilmiah saja, bahkan ada yang menyoal kalau mau bicara politik sebaiknya jangan di group ini, keluar saja dan lain sebagainya.
Hal itu adalah bukti betapa rendahnya tingkat literasi demokrasi masyarakat kita. Ironisnya, itu justru, terjadi di kalangan intelektual. Kaum intelektual seharusnya peduli terhadap perbincangan isu-isu politik.
Karena politik adalah penyebab susah atau senang nasib rakyat. Ingat, politik bukan sekadar soal memilih individu untuk jabatan esekutif tertinggi. Tetapi, politik itu harus dipahami secara esensinya.
Yakni, politik adalah cara bagaimana mengatur urusan rakyat. Urusan rakyat adalah masalah yang sangat vital. Karena itu menyangkut nasib mereka dalam mendapatkan hak-hak dan kesejahteran sebagai warga negara yang telah membayar pajak.
Karena itu, kesempatan bagi intelektual untuk menyoal, mendebatkan dan menguliti visi, misi dan program-program paslon presiden dan wakil presiden bagaimana mereka akan membawa perubahan untuk bangsa dan negara ke depan.
Kaum intelektual seharusnya aktif memberikan analisis tajamnya sebagai bentuk kritikan dan pencerahan kepada masyarakat. Tentunya, sorotan dari aneka disiplin ilmu dan perspektif sangat perlu dilontarkan ke tengah publik yang haus akan ide-ide segar.
Kritik tidak hanya menyangkut soal kesejahteraan, tetapi juga dapat yang lebih dalam lagi, yakni seperti kritik struktural dalam berdemokrasi. Bisakah demokrasi membawa kesejahteraan masyarakat yang hakiki, lahir dan batin?
Demokrasi Tak Sekadar Memilih Pemimpin
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang lahir dari konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan. Menurut konsep dasar demokrasi, pemerintahan diatur dan dipilih oleh rakyat sendiri.
Seluruh rakyat harus berkumpul di suatu tempat umum. Mereka kemudian membuat konstitusi dan undang-undang yang akan diberlakukan untuk mengatur berbagai urusan, serta membuat keputusan terhadap masalah yang perlu diselesaikan.
Namun, dikarenakan seluruh rakyat tidak mungkin melakukan itu, maka dipilihlah wakil-wakil dari kalangan mereka. Para wakil itulah yang akan mewakili mereka untuk mengisi Lembaga Legislatif.
Lembaga itu yang nantinya disebut sebagai dewan perwakilan rakyat. Pada hakikatnya, demokrasi dilandaskan pada gagasan prinsip, yakni kedaulatan di tangan rakyat (tidak lagi ditangan raja), dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan.
Pada awalnya, kemunculan demokrasi sebagai bentuk sikap anti tesis dari sistem pemerintahan feodalisme otoriter yang dilegitimasi oleh kaum agamawan.
Kesadaran yang tumbuh dan berkembang di kalangan kaum intelektual untuk menolak bersatunya raja dan agamawan yang menindas rakyatnya. Pada saat itu, agamawan cenderung melegitimasi apapun yang dilakukan dan dikehendaki raja. Dengan mengatasnamakan wakil tuhan di bumi para raja telah menjadikan rakyat sebagai sapi perah dan budak untuk kesenangan para bangsawan dan kerabat mereka.
Para filsuf dan pemikir di Eropa pada saat itu, melawan para kaisar dan raja untuk menghapuskan ide tentang hak ketuhanan (Divine Rights) yang mendominasi Eropa. Melalui gagasan itu, para raja dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak membuat peraturan serta menyelenggarakan pemerintahan dan pengadilan sekaligus.
Kaisar atau raja adalah negara itu sendiri (l’etat, c’est mo). Dalam sistem itu, rakyat hanya dianggap sebagai budak yang tidak memiliki hak berpendapat atau berkehendak. Kewajiban mereka hanya tunduk dan patuh pada raja saja.
Itu gambaran idealisme demokrasi dalam konsep dasarnya. Akan tetapi, jika kita perhatikan fakta lapangan yang terjadi justru demokrasi itu telah dibajak oleh golongan minoritas, mereka itu adalah golongan oligarki.
Hal itu dapat dilihat bagaimana mereka mengendalikan semua sektor ekonomi dan politik. Kekuatan ekonomi mereka telah menjelma sebagai representasi simbol kekuasaan. Dengan sumber keuangan yang luar biasa besar, para oligarki dapat mengendalikan aktor-aktor politik dengan mudah. Tujuannya supaya aktor politik itu dapat berkompromi dengan mereka.
Setelah itu, mereka dapat mendapatkan kue ekonomi lebih besar lagi. Dengan penguasaan sumber ekonomi itu, mereka dapat mengendalikan arah politik negara hanya demi kepentingan dan eksistensi kelompoknya.
Itulah bahaya kelemahan dalam sistem demokrasi. Sebab standar ukuran baik buruk dalam sistem demokrasi hanya berdasarkan asas manfaat.
Dengan demikian, perilaku menghalalkan segala cara (Machiavellisme) menjadi hal yang lumrah dalam sistem ini. jika kita mau berpikir lebih jernih dan sedikit mendalam, maka demokrasi bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan juga terkait dengan yang berhak membuat hukum atau peraturan.
Kenyataanya, pembuatan undang-undang tidak dilakukan oleh rakyat langsung melainkan dilaksanakan oleh wakil rakyat dan pemerintah. Itupun dalam pembuatan undang-undang ada kemungkinan dapat dikendalikan oleh kelompok oligarki itu.
Dengan kekuatan modal, mereka dapat melakukan lobi-lobi dan manuver politik untuk menjaga kepentingannya. Hal itu dibuktikan dengan beberapa rancangan undang-undang dengan simsalabim dalam waktu singkat telah disahkan, serta tidak ada hearing public yang cukup. Contohnya UU Minerba, UU Omnibuslaw Cipta Kerja, dan masih banyak yang lain.
Walhasil, demokrasi dapat berubah menjadi otokrasi jika didukung dan dilegalisasi oleh oligarki, partai-partai politik, dan penjaga sistem itu sendiri.
Oleh karena itu sikap kritis kalangan intelektual dan kewarasan berpolitik terus dibutuhkan untuk digaungkan dan didiskusikan, serta secara konsisten mengkritisi sistem politik dan penerapannya. (*)