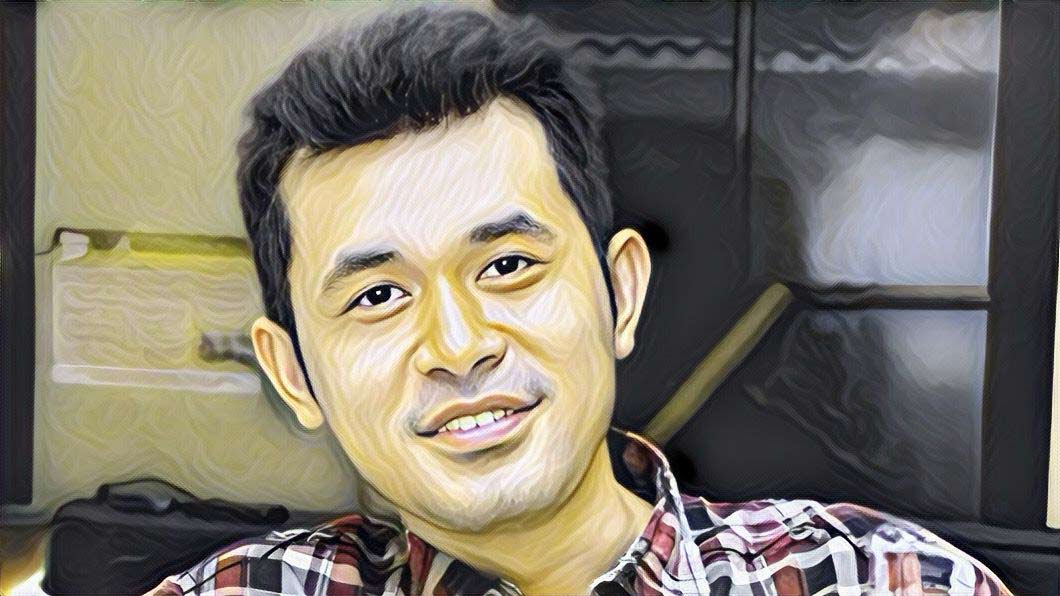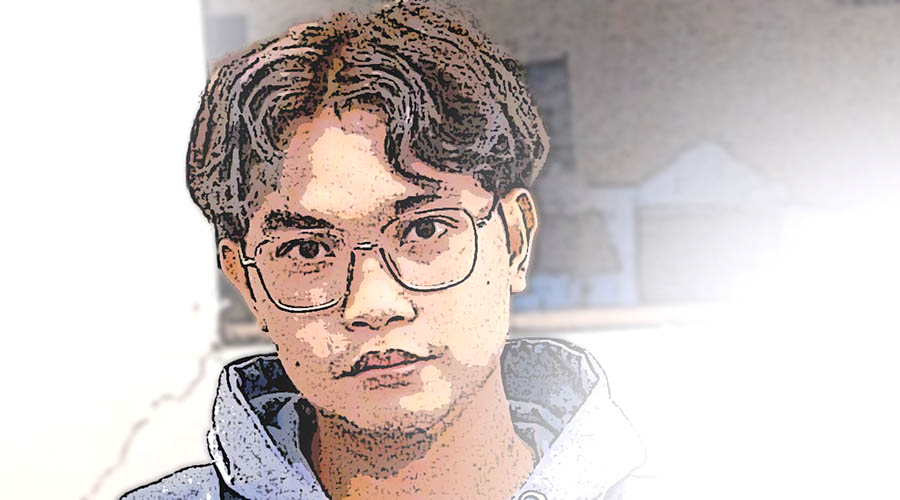SAYA sangat tergelitik saat setahun yang lalu membaca sebuah artikel di sebuah media. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa sistem pendidikan kita kurang maju disebabkan pandangan keagamaan yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia.
Penulisnya mengkritisi fenomena pemahaman keagamaan yang seperti itu sebagai menjadi penyebab turunnya minat dan semangat siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ketrampilan hidup (baca:
life skills).
Para agamawan dianggap kurang responsif terhadap mutu pendidikan kita terutama di bidang sains dan teknologi hanya karena posisi ranking PISA (
Programme for International Students Asassment) negeri kita sering di posisi bawah, yakni urutan 62 dari 70 negara. PISA adalah asesmen yang menilai tingkat literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sains.
Dengan hasil yang masih rendah itu, kita sudah dianggap seolah-olah kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam semua bidang. Saya kira penarikan simpulan seperti itu terlalu terburu-buru dan agak gegabah.
Memang membicarakan mutu pendidikan bukanlah suatu yang gampang. Hal itu dikarenakan banyak faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, sebetulnya yang kita butuhkan sumber daya manusia seperti apa?, model pendidikan yang bagaimana?.
Jika, kita cermati misi pembangunan pemerintah Jokowi periode kedua saat ini, yaitu mengutamakan pembangunan SDM Indonesia, maka kita segera dapat menangkap arah pendidikan negeri ini lima tahun ke depan, yakni pembangunan manusia Indonesia unggul. Lalu keunggulan seperti apa yang kita inginkan. Keunggulan dalam pengusaan sains dan teknologi (baca: ketrampilan) tanpa karakter, atau pendidikan ketrampilan plus karakter?.
Karakter dan SkillPada Abad ke-21 ini. Ada beberapa jenis keterampilan yang harus dikuasai lulusan sekolah kita jika mereka ingin dapat berkompetisi dengan SDM asing, yaitu yang disingkat dengan 4 K; Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir Kritis dan Pemecah Masalah, serta Kreativitas dan inovasi. 4 kompetensi itulah yang dikenal dengan
soft skill. Di samping itu
hard skill (pengetahuan dan ketrampilan) juga tak kalah pentingya, karena itu sebagai tolak ukur profesionalisme seseorang dalam bidang keahliannya.
Gabungan keduanya akan membawa SDM kita unggul terlebih lagi jika diperkuat dengan karakter yang mulia, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, berperilaku jujur, antikorupsi. Dan tentunya itu semua didasarkan pada keimanan yang kuat dan kokoh.
Artinya tatkala karakter dan
skill dijadikan patokan perumusan muatan pendidikan, tentunya dapat dihasilkan generasi dengan profil terampil sekaligus berkarakter mulia. Sosok generasi seperti itulah yang dapat diharapkan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi.
Oleh karena itu, pendidikan kita seharusnya diarahkan untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan ketrampilan hidup (
life skill) dengan pendidikan karakter (
character building). Keduanya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan manusia Indonesia unggul.
Hanya saja, persepsi guru tentang hal itu masih beraneka ragam sehingga berdampak pada implementasi di lapangan yang berbeda-beda pula. Hal itu, tentu saja dapat membingungkan siswa dan orang tua. Ada yang menganggap pendidikan karakter dilakukan dengan agamisasi kurikulum.
Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Uswatun Qoyyimah dkk dalam artikel yang bertajuk
Professional Identity and Imagined Student Identity of EIL Teachers in Islamic Schools dalam Journal of language, identity & Education.Penelitian itu menyimpulkan bahwa guru-guru bahasa Inggris di sekolah swasta Islam memiliki persepsi indentitas profesional guru yang utama adalah sebagai penjaga gawang moral (
care giver and moral guardian) daripada sebagai guru bahasa Inggris (baca:
skill). Para guru memiliki kecenderungan pemahaman bahasa Inggris cukup sebagai wahana pendidikan agama (baca: karakter), sedangkan aspek keterampilan dan budaya agak terabaikan.Alasannya, anak didik mereka bisa terpengaruh budaya luar dan takut lunturnya nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal itu berdampak pada ketrampilan berbahasa siswa jauh dari harapan yang semestinya.Padahal dalam berbahasa, pengetahuan bahasa dan budaya sangat dibutuhkan agar komunikasi dapat berjalan baik. Fakta menunjukkan rata-rata lulusan sekolah belum memiliki kompetensi komunikasi yang cukup supaya mampu ikut terlibat dalam pergaulan dan perbincangan internasional.
Guru Intelektual TransformativeSebagai garda terdepan dalam meningkatkan SDM Indonesia, guru adalah intelektual transformative, yakni memiliki peran sangat penting dalam pengembangan intelektualitas dan karakter siswa menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekadar mentranfer pengetahuan (baca: kognitif) melainkan juga mewujudkan nilai-nilai karakter yang dapat mendorong siswa dengan mudah beradaptasi pada waktu dan tempat sesuai perubahan zaman di masa depan.Guru juga dapat berfungsi sebagai pemimpin perubahan sosial tanpa revolusi fisik sebagaimana yang dikatakan oleh Gramsci. Dari sini penting untuk mengetahui persepsi guru tentang identitas profesional guru dan identitas siswa yang diimpikannya.Menurut saya perlu diadakan evaluasi yang komprehensif terhadap pemahaman guru tentang pendidikan berbasis kompetensi dan karakter (baca: K-13). Ternyata, di lapangan, guru lebih memilih mengedepankan pendidikan karakter (baca: agama ritual) daripada keterampilan atau
skill siswa.Tentunya, itu kontradiksi dengan kebijakan pemerintah agar lulusan sekolah memiliki kompetensi keterampilan, sekaligus berkarakter mulia. Sehingga kelak setelah lulus, siswa memiliki jiwa mandiri dan tangguh dalam mengadapi di era disrupsi saat ini.Walhasil, pemerintah (baca: Kemendikbudristek) perlu segera mengambil sebuah kebijakan teknis guna membantu para guru dalam mengembangkan kurikulum yang mencakupi kompetensi keterampilan dan karakter secara bersamaan, serta bagaimana teknis dan prosedur pengajaran yang efektif dan berdampak. Dengan demikian, problema pendidikan dapat segera teratasi demi daya saing SDM Indonesia di masa depan. (*)
*) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus
[caption id="attachment_271807" align="alignleft" width="150"]

Ahdi Riyono *)[/caption]
SAYA sangat tergelitik saat setahun yang lalu membaca sebuah artikel di sebuah media. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa sistem pendidikan kita kurang maju disebabkan pandangan keagamaan yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia.
Penulisnya mengkritisi fenomena pemahaman keagamaan yang seperti itu sebagai menjadi penyebab turunnya minat dan semangat siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ketrampilan hidup (baca:
life skills).
Para agamawan dianggap kurang responsif terhadap mutu pendidikan kita terutama di bidang sains dan teknologi hanya karena posisi ranking PISA (
Programme for International Students Asassment) negeri kita sering di posisi bawah, yakni urutan 62 dari 70 negara. PISA adalah asesmen yang menilai tingkat literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sains.
Dengan hasil yang masih rendah itu, kita sudah dianggap seolah-olah kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam semua bidang. Saya kira penarikan simpulan seperti itu terlalu terburu-buru dan agak gegabah.
Memang membicarakan mutu pendidikan bukanlah suatu yang gampang. Hal itu dikarenakan banyak faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, sebetulnya yang kita butuhkan sumber daya manusia seperti apa?, model pendidikan yang bagaimana?.
Jika, kita cermati misi pembangunan pemerintah Jokowi periode kedua saat ini, yaitu mengutamakan pembangunan SDM Indonesia, maka kita segera dapat menangkap arah pendidikan negeri ini lima tahun ke depan, yakni pembangunan manusia Indonesia unggul. Lalu keunggulan seperti apa yang kita inginkan. Keunggulan dalam pengusaan sains dan teknologi (baca: ketrampilan) tanpa karakter, atau pendidikan ketrampilan plus karakter?.
Karakter dan Skill
Pada Abad ke-21 ini. Ada beberapa jenis keterampilan yang harus dikuasai lulusan sekolah kita jika mereka ingin dapat berkompetisi dengan SDM asing, yaitu yang disingkat dengan 4 K; Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir Kritis dan Pemecah Masalah, serta Kreativitas dan inovasi. 4 kompetensi itulah yang dikenal dengan
soft skill. Di samping itu
hard skill (pengetahuan dan ketrampilan) juga tak kalah pentingya, karena itu sebagai tolak ukur profesionalisme seseorang dalam bidang keahliannya.
Gabungan keduanya akan membawa SDM kita unggul terlebih lagi jika diperkuat dengan karakter yang mulia, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, berperilaku jujur, antikorupsi. Dan tentunya itu semua didasarkan pada keimanan yang kuat dan kokoh.
Artinya tatkala karakter dan
skill dijadikan patokan perumusan muatan pendidikan, tentunya dapat dihasilkan generasi dengan profil terampil sekaligus berkarakter mulia. Sosok generasi seperti itulah yang dapat diharapkan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi.
Oleh karena itu, pendidikan kita seharusnya diarahkan untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan ketrampilan hidup (
life skill) dengan pendidikan karakter (
character building). Keduanya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan manusia Indonesia unggul.
Hanya saja, persepsi guru tentang hal itu masih beraneka ragam sehingga berdampak pada implementasi di lapangan yang berbeda-beda pula. Hal itu, tentu saja dapat membingungkan siswa dan orang tua. Ada yang menganggap pendidikan karakter dilakukan dengan agamisasi kurikulum.
Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Uswatun Qoyyimah dkk dalam artikel yang bertajuk
Professional Identity and Imagined Student Identity of EIL Teachers in Islamic Schools dalam Journal of language, identity & Education.
Penelitian itu menyimpulkan bahwa guru-guru bahasa Inggris di sekolah swasta Islam memiliki persepsi indentitas profesional guru yang utama adalah sebagai penjaga gawang moral (
care giver and moral guardian) daripada sebagai guru bahasa Inggris (baca:
skill). Para guru memiliki kecenderungan pemahaman bahasa Inggris cukup sebagai wahana pendidikan agama (baca: karakter), sedangkan aspek keterampilan dan budaya agak terabaikan.
Alasannya, anak didik mereka bisa terpengaruh budaya luar dan takut lunturnya nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal itu berdampak pada ketrampilan berbahasa siswa jauh dari harapan yang semestinya.
Padahal dalam berbahasa, pengetahuan bahasa dan budaya sangat dibutuhkan agar komunikasi dapat berjalan baik. Fakta menunjukkan rata-rata lulusan sekolah belum memiliki kompetensi komunikasi yang cukup supaya mampu ikut terlibat dalam pergaulan dan perbincangan internasional.
Guru Intelektual Transformative
Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan SDM Indonesia, guru adalah intelektual transformative, yakni memiliki peran sangat penting dalam pengembangan intelektualitas dan karakter siswa menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekadar mentranfer pengetahuan (baca: kognitif) melainkan juga mewujudkan nilai-nilai karakter yang dapat mendorong siswa dengan mudah beradaptasi pada waktu dan tempat sesuai perubahan zaman di masa depan.
Guru juga dapat berfungsi sebagai pemimpin perubahan sosial tanpa revolusi fisik sebagaimana yang dikatakan oleh Gramsci. Dari sini penting untuk mengetahui persepsi guru tentang identitas profesional guru dan identitas siswa yang diimpikannya.
Menurut saya perlu diadakan evaluasi yang komprehensif terhadap pemahaman guru tentang pendidikan berbasis kompetensi dan karakter (baca: K-13). Ternyata, di lapangan, guru lebih memilih mengedepankan pendidikan karakter (baca: agama ritual) daripada keterampilan atau
skill siswa.
Tentunya, itu kontradiksi dengan kebijakan pemerintah agar lulusan sekolah memiliki kompetensi keterampilan, sekaligus berkarakter mulia. Sehingga kelak setelah lulus, siswa memiliki jiwa mandiri dan tangguh dalam mengadapi di era disrupsi saat ini.
Walhasil, pemerintah (baca: Kemendikbudristek) perlu segera mengambil sebuah kebijakan teknis guna membantu para guru dalam mengembangkan kurikulum yang mencakupi kompetensi keterampilan dan karakter secara bersamaan, serta bagaimana teknis dan prosedur pengajaran yang efektif dan berdampak. Dengan demikian, problema pendidikan dapat segera teratasi demi daya saing SDM Indonesia di masa depan. (*)
*) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus





 Ahdi Riyono *)[/caption]
SAYA sangat tergelitik saat setahun yang lalu membaca sebuah artikel di sebuah media. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa sistem pendidikan kita kurang maju disebabkan pandangan keagamaan yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia.
Penulisnya mengkritisi fenomena pemahaman keagamaan yang seperti itu sebagai menjadi penyebab turunnya minat dan semangat siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ketrampilan hidup (baca: life skills).
Para agamawan dianggap kurang responsif terhadap mutu pendidikan kita terutama di bidang sains dan teknologi hanya karena posisi ranking PISA (Programme for International Students Asassment) negeri kita sering di posisi bawah, yakni urutan 62 dari 70 negara. PISA adalah asesmen yang menilai tingkat literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sains.
Dengan hasil yang masih rendah itu, kita sudah dianggap seolah-olah kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam semua bidang. Saya kira penarikan simpulan seperti itu terlalu terburu-buru dan agak gegabah.
Memang membicarakan mutu pendidikan bukanlah suatu yang gampang. Hal itu dikarenakan banyak faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, sebetulnya yang kita butuhkan sumber daya manusia seperti apa?, model pendidikan yang bagaimana?.
Jika, kita cermati misi pembangunan pemerintah Jokowi periode kedua saat ini, yaitu mengutamakan pembangunan SDM Indonesia, maka kita segera dapat menangkap arah pendidikan negeri ini lima tahun ke depan, yakni pembangunan manusia Indonesia unggul. Lalu keunggulan seperti apa yang kita inginkan. Keunggulan dalam pengusaan sains dan teknologi (baca: ketrampilan) tanpa karakter, atau pendidikan ketrampilan plus karakter?.
Karakter dan Skill
Pada Abad ke-21 ini. Ada beberapa jenis keterampilan yang harus dikuasai lulusan sekolah kita jika mereka ingin dapat berkompetisi dengan SDM asing, yaitu yang disingkat dengan 4 K; Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir Kritis dan Pemecah Masalah, serta Kreativitas dan inovasi. 4 kompetensi itulah yang dikenal dengan soft skill. Di samping itu hard skill (pengetahuan dan ketrampilan) juga tak kalah pentingya, karena itu sebagai tolak ukur profesionalisme seseorang dalam bidang keahliannya.
Gabungan keduanya akan membawa SDM kita unggul terlebih lagi jika diperkuat dengan karakter yang mulia, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, berperilaku jujur, antikorupsi. Dan tentunya itu semua didasarkan pada keimanan yang kuat dan kokoh.
Artinya tatkala karakter dan skill dijadikan patokan perumusan muatan pendidikan, tentunya dapat dihasilkan generasi dengan profil terampil sekaligus berkarakter mulia. Sosok generasi seperti itulah yang dapat diharapkan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi.
Oleh karena itu, pendidikan kita seharusnya diarahkan untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan ketrampilan hidup (life skill) dengan pendidikan karakter (character building). Keduanya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan manusia Indonesia unggul.
Hanya saja, persepsi guru tentang hal itu masih beraneka ragam sehingga berdampak pada implementasi di lapangan yang berbeda-beda pula. Hal itu, tentu saja dapat membingungkan siswa dan orang tua. Ada yang menganggap pendidikan karakter dilakukan dengan agamisasi kurikulum.
Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Uswatun Qoyyimah dkk dalam artikel yang bertajuk Professional Identity and Imagined Student Identity of EIL Teachers in Islamic Schools dalam Journal of language, identity & Education.
Penelitian itu menyimpulkan bahwa guru-guru bahasa Inggris di sekolah swasta Islam memiliki persepsi indentitas profesional guru yang utama adalah sebagai penjaga gawang moral (care giver and moral guardian) daripada sebagai guru bahasa Inggris (baca: skill). Para guru memiliki kecenderungan pemahaman bahasa Inggris cukup sebagai wahana pendidikan agama (baca: karakter), sedangkan aspek keterampilan dan budaya agak terabaikan.
Alasannya, anak didik mereka bisa terpengaruh budaya luar dan takut lunturnya nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal itu berdampak pada ketrampilan berbahasa siswa jauh dari harapan yang semestinya.
Padahal dalam berbahasa, pengetahuan bahasa dan budaya sangat dibutuhkan agar komunikasi dapat berjalan baik. Fakta menunjukkan rata-rata lulusan sekolah belum memiliki kompetensi komunikasi yang cukup supaya mampu ikut terlibat dalam pergaulan dan perbincangan internasional.
Guru Intelektual Transformative
Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan SDM Indonesia, guru adalah intelektual transformative, yakni memiliki peran sangat penting dalam pengembangan intelektualitas dan karakter siswa menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekadar mentranfer pengetahuan (baca: kognitif) melainkan juga mewujudkan nilai-nilai karakter yang dapat mendorong siswa dengan mudah beradaptasi pada waktu dan tempat sesuai perubahan zaman di masa depan.
Guru juga dapat berfungsi sebagai pemimpin perubahan sosial tanpa revolusi fisik sebagaimana yang dikatakan oleh Gramsci. Dari sini penting untuk mengetahui persepsi guru tentang identitas profesional guru dan identitas siswa yang diimpikannya.
Menurut saya perlu diadakan evaluasi yang komprehensif terhadap pemahaman guru tentang pendidikan berbasis kompetensi dan karakter (baca: K-13). Ternyata, di lapangan, guru lebih memilih mengedepankan pendidikan karakter (baca: agama ritual) daripada keterampilan atau skill siswa.
Tentunya, itu kontradiksi dengan kebijakan pemerintah agar lulusan sekolah memiliki kompetensi keterampilan, sekaligus berkarakter mulia. Sehingga kelak setelah lulus, siswa memiliki jiwa mandiri dan tangguh dalam mengadapi di era disrupsi saat ini.
Walhasil, pemerintah (baca: Kemendikbudristek) perlu segera mengambil sebuah kebijakan teknis guna membantu para guru dalam mengembangkan kurikulum yang mencakupi kompetensi keterampilan dan karakter secara bersamaan, serta bagaimana teknis dan prosedur pengajaran yang efektif dan berdampak. Dengan demikian, problema pendidikan dapat segera teratasi demi daya saing SDM Indonesia di masa depan. (*)
*) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus
Ahdi Riyono *)[/caption]
SAYA sangat tergelitik saat setahun yang lalu membaca sebuah artikel di sebuah media. Dalam artikel tersebut, dinyatakan bahwa sistem pendidikan kita kurang maju disebabkan pandangan keagamaan yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia.
Penulisnya mengkritisi fenomena pemahaman keagamaan yang seperti itu sebagai menjadi penyebab turunnya minat dan semangat siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ketrampilan hidup (baca: life skills).
Para agamawan dianggap kurang responsif terhadap mutu pendidikan kita terutama di bidang sains dan teknologi hanya karena posisi ranking PISA (Programme for International Students Asassment) negeri kita sering di posisi bawah, yakni urutan 62 dari 70 negara. PISA adalah asesmen yang menilai tingkat literasi siswa dalam membaca, matematika, dan sains.
Dengan hasil yang masih rendah itu, kita sudah dianggap seolah-olah kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam semua bidang. Saya kira penarikan simpulan seperti itu terlalu terburu-buru dan agak gegabah.
Memang membicarakan mutu pendidikan bukanlah suatu yang gampang. Hal itu dikarenakan banyak faktor dan variabel yang mempengaruhinya. Sebagai contoh, sebetulnya yang kita butuhkan sumber daya manusia seperti apa?, model pendidikan yang bagaimana?.
Jika, kita cermati misi pembangunan pemerintah Jokowi periode kedua saat ini, yaitu mengutamakan pembangunan SDM Indonesia, maka kita segera dapat menangkap arah pendidikan negeri ini lima tahun ke depan, yakni pembangunan manusia Indonesia unggul. Lalu keunggulan seperti apa yang kita inginkan. Keunggulan dalam pengusaan sains dan teknologi (baca: ketrampilan) tanpa karakter, atau pendidikan ketrampilan plus karakter?.
Karakter dan Skill
Pada Abad ke-21 ini. Ada beberapa jenis keterampilan yang harus dikuasai lulusan sekolah kita jika mereka ingin dapat berkompetisi dengan SDM asing, yaitu yang disingkat dengan 4 K; Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir Kritis dan Pemecah Masalah, serta Kreativitas dan inovasi. 4 kompetensi itulah yang dikenal dengan soft skill. Di samping itu hard skill (pengetahuan dan ketrampilan) juga tak kalah pentingya, karena itu sebagai tolak ukur profesionalisme seseorang dalam bidang keahliannya.
Gabungan keduanya akan membawa SDM kita unggul terlebih lagi jika diperkuat dengan karakter yang mulia, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, berperilaku jujur, antikorupsi. Dan tentunya itu semua didasarkan pada keimanan yang kuat dan kokoh.
Artinya tatkala karakter dan skill dijadikan patokan perumusan muatan pendidikan, tentunya dapat dihasilkan generasi dengan profil terampil sekaligus berkarakter mulia. Sosok generasi seperti itulah yang dapat diharapkan membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan berperadaban tinggi.
Oleh karena itu, pendidikan kita seharusnya diarahkan untuk tidak mendikotomikan antara pendidikan ketrampilan hidup (life skill) dengan pendidikan karakter (character building). Keduanya sangat dibutuhkan untuk menghasilkan manusia Indonesia unggul.
Hanya saja, persepsi guru tentang hal itu masih beraneka ragam sehingga berdampak pada implementasi di lapangan yang berbeda-beda pula. Hal itu, tentu saja dapat membingungkan siswa dan orang tua. Ada yang menganggap pendidikan karakter dilakukan dengan agamisasi kurikulum.
Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian Uswatun Qoyyimah dkk dalam artikel yang bertajuk Professional Identity and Imagined Student Identity of EIL Teachers in Islamic Schools dalam Journal of language, identity & Education.
Penelitian itu menyimpulkan bahwa guru-guru bahasa Inggris di sekolah swasta Islam memiliki persepsi indentitas profesional guru yang utama adalah sebagai penjaga gawang moral (care giver and moral guardian) daripada sebagai guru bahasa Inggris (baca: skill). Para guru memiliki kecenderungan pemahaman bahasa Inggris cukup sebagai wahana pendidikan agama (baca: karakter), sedangkan aspek keterampilan dan budaya agak terabaikan.
Alasannya, anak didik mereka bisa terpengaruh budaya luar dan takut lunturnya nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal itu berdampak pada ketrampilan berbahasa siswa jauh dari harapan yang semestinya.
Padahal dalam berbahasa, pengetahuan bahasa dan budaya sangat dibutuhkan agar komunikasi dapat berjalan baik. Fakta menunjukkan rata-rata lulusan sekolah belum memiliki kompetensi komunikasi yang cukup supaya mampu ikut terlibat dalam pergaulan dan perbincangan internasional.
Guru Intelektual Transformative
Sebagai garda terdepan dalam meningkatkan SDM Indonesia, guru adalah intelektual transformative, yakni memiliki peran sangat penting dalam pengembangan intelektualitas dan karakter siswa menjadi manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekadar mentranfer pengetahuan (baca: kognitif) melainkan juga mewujudkan nilai-nilai karakter yang dapat mendorong siswa dengan mudah beradaptasi pada waktu dan tempat sesuai perubahan zaman di masa depan.
Guru juga dapat berfungsi sebagai pemimpin perubahan sosial tanpa revolusi fisik sebagaimana yang dikatakan oleh Gramsci. Dari sini penting untuk mengetahui persepsi guru tentang identitas profesional guru dan identitas siswa yang diimpikannya.
Menurut saya perlu diadakan evaluasi yang komprehensif terhadap pemahaman guru tentang pendidikan berbasis kompetensi dan karakter (baca: K-13). Ternyata, di lapangan, guru lebih memilih mengedepankan pendidikan karakter (baca: agama ritual) daripada keterampilan atau skill siswa.
Tentunya, itu kontradiksi dengan kebijakan pemerintah agar lulusan sekolah memiliki kompetensi keterampilan, sekaligus berkarakter mulia. Sehingga kelak setelah lulus, siswa memiliki jiwa mandiri dan tangguh dalam mengadapi di era disrupsi saat ini.
Walhasil, pemerintah (baca: Kemendikbudristek) perlu segera mengambil sebuah kebijakan teknis guna membantu para guru dalam mengembangkan kurikulum yang mencakupi kompetensi keterampilan dan karakter secara bersamaan, serta bagaimana teknis dan prosedur pengajaran yang efektif dan berdampak. Dengan demikian, problema pendidikan dapat segera teratasi demi daya saing SDM Indonesia di masa depan. (*)
*) Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muria Kudus