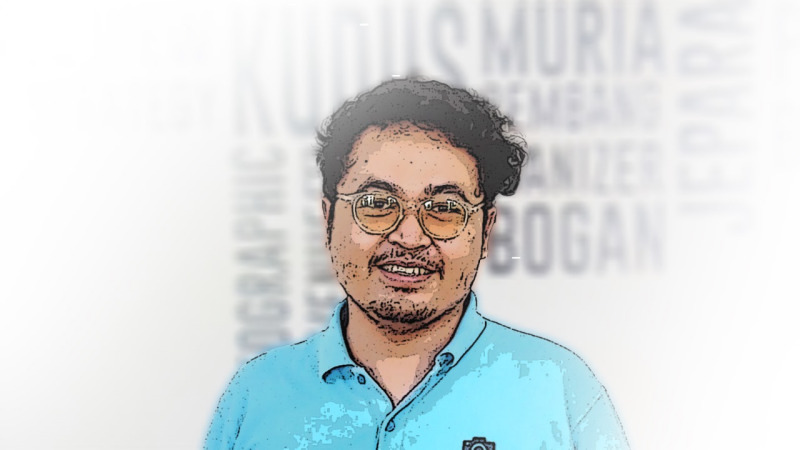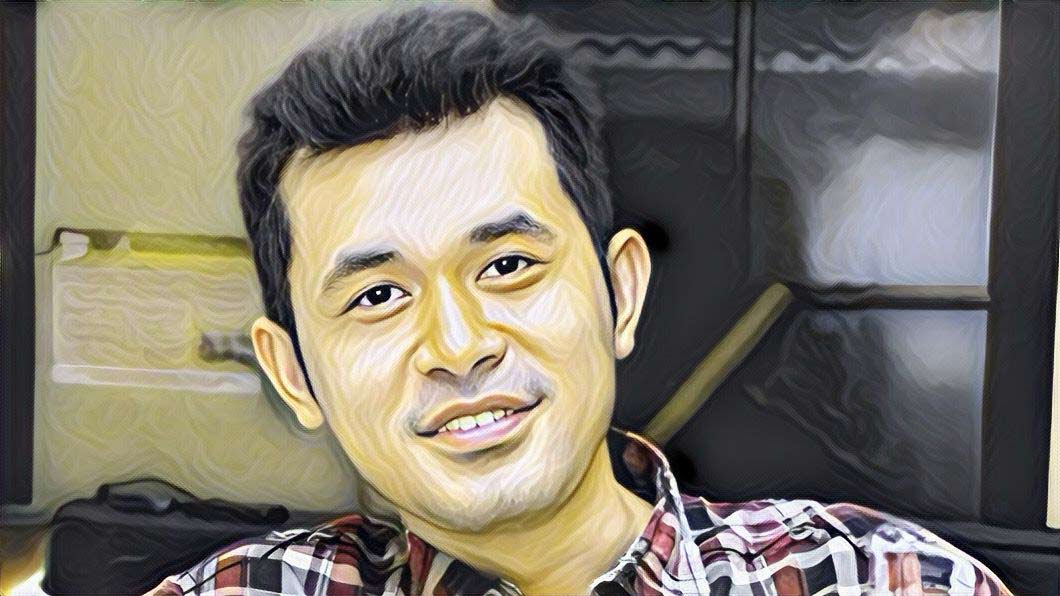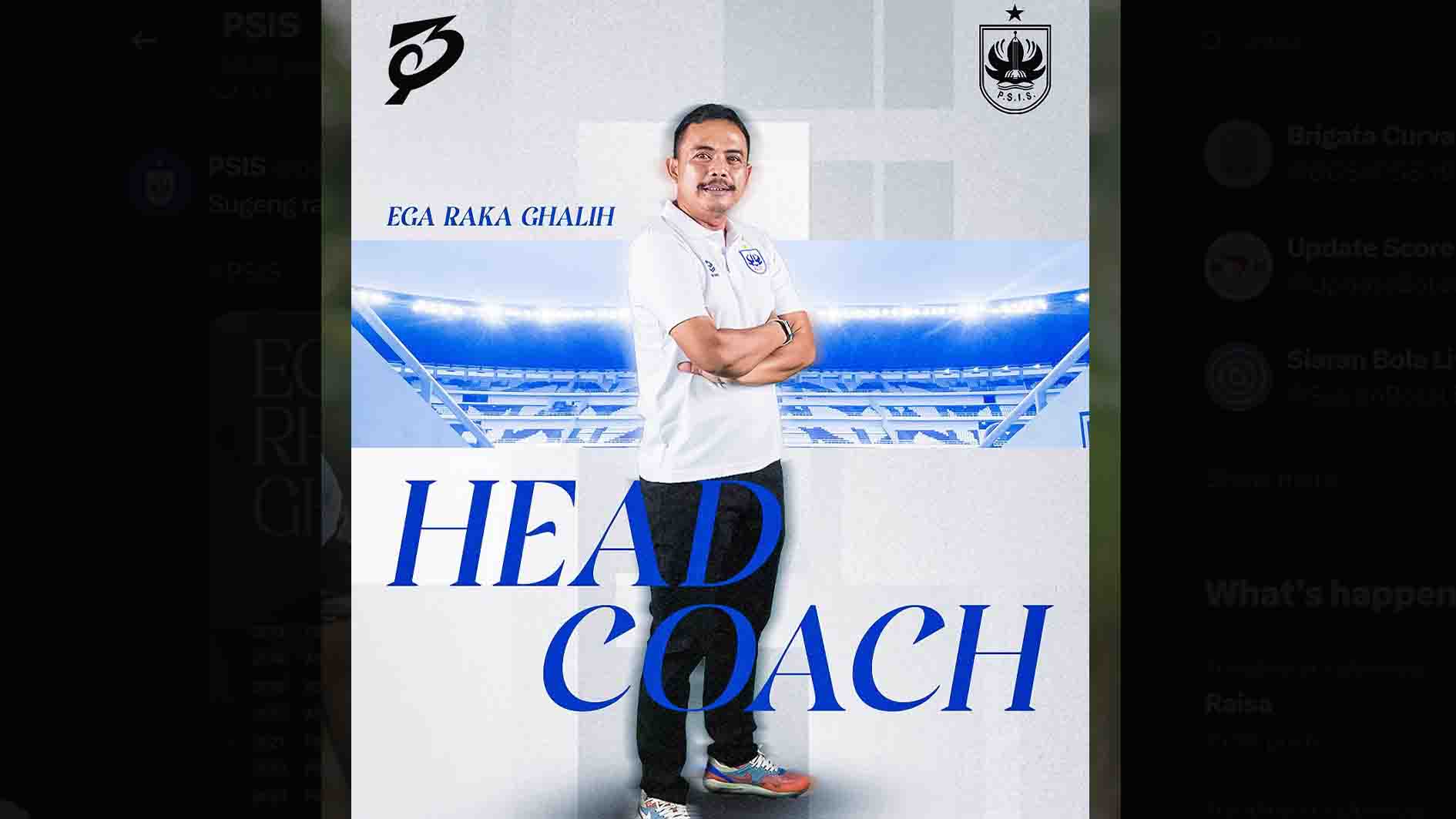Pangan: Sastra dan Berita
Murianews
Sabtu, 29 Oktober 2022 06:00:09
PADA masa lalu, krisis pangan biasa terjadi. Catatan-catatan sejarah bersumber masa kerajaan dan kolonial mengabarkan sulit pangan dan kelaparan terjadi di Nusantara. Ingatan-ingatan belum menghilang malah ditambahi dengan beragam berita dan artikel mengenai krisis pangan global. Konon, pemicu terbesar itu perang Rusia dan Ukraina.
Kita mengerti tapi membawa bingung-bingung sejak lama. Di Indonesia, krisis pangan terjadi tapi pidato atau jawaban penguasa dan kaum politik sering klise. Sekian catatan sejarah justru memunculkan kemahiran elite mengaburkan dan mengganti masalah-masalah dalam krisis pangan.
Krisis terjadi tapi ajaran-ajaran pangan tetap disampaikan para leluhur. Para pujangga menulis pelbagai cerita mengandung pesan-pesan pertanian dan adab makan. Urusan pangan mengikutkan persoalan-persoalan iman, politik, estetika, etika, perdagangan, dan lain-lain.
Kita mengutip dari
Serat Sanasunu gubahan Yasadipura II dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia: ”Janganlah menganggap ringan masalah makan sehingga tidak perlu dipikirkan… Masalah orang makan adalah masalah baku karena makan menjadi pengikat kehidupan”.
Di situ, pembaca tak mendapat pengisahan atau penjelasan beragam jenis pangan disantap orang-orang di Jawa dan diusahakan dalam pertanian.
Di buku berjudul
Ijtihad Progresif Yasadipura II dalam Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa (2004) susunan Sri Suhandjati Sukri, kita mendapat penjelasan:
”Mengingat pentingnya mengurangi makan bagi kewaspadaan batin di kalangan orang Jawa, masalah makan mendapat perhatian raja maupun pujangga, seperti tampak dalam
Serat Sanasunu dan
Wulangreh. Kekhawatiran atas terjadinya perubahan tata cara makan bagi orang Jawa karena pengaruh budaya Barat, mendorong Yasadipura II mengajarkan tata krama makan sebagaimana dilakukan Rasululullah”.
Kita tak sedang berpikiran krisis pangan. Serat itu mengingatkan tentang prihatin, tirakat, dan pemaknaan makan. Pada masa lalu, krisis pangan mungkin terjadi tapi orang sudah belajar menjadi sabar dengan mengurangi makan atau berpuasa. Kita mencomot penjelasan silam agar tak terlalu ketakutan bila diserbu berita-berita tentang krisis pangan global. Kita mungkin mula-mula menganggap itu terlalu politis dan bisnis.
Di
Kompas, 13 Oktober 2022, tajuk rencana mengenai pangan. Kita mengutip: ”Bertahun-tahun kita mendengungkan konsumsi pangan lokal, tetapi urusan ini tak pernah berujung pada satu aksi nyata dalam jangka panjang. kampanye pangan lokal masih sekadar menjadi slogan. Kini saatnya membuat ajakan memproduksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi riil. Keterpepetan karena krisis pangan yang ditandai dengan lonjakan harga pangan sudah selayaknya melecut semua pihak untuk melirik komoditas pangan setempat”.
Selama puluhan tahun, kita mendapat ”pelajaran” dan ”perintah” untuk menikmati makanan-makanan bukan lokal. Kita diajak menjadi konsumen global. Selera dibentuk dengan “indah”, “manis”, dan “baik”.Jutaan orang menuruti selera sampai dalam pertaruhan harga (diri) dan “kebahagiaan”. Kita mungkin susah ingkar bila mulai kehilangan ilmu pangan dari para leluhur. Pengetahuan tentang pangan lokal pun jarang menjadi tema besar dalam pelajaran di sekolah dan percakapan-percakapan di ruang publik.Sejak masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, sekian janji besar dan kebijakan sulit mewujudkan kedaulatan pangan (lokal). Pidato-pidato sudah disampaikan dengan menggebu dan kalem. Puluhan slogan dibuat untuk diucapkan bersama tanpa perjanjian terwujud. Kliping berita selalu mengingatkan bila pangan lokal itu kebablasan menjadi bualan kaum elite dan pemilik modal.Pada hari-hari setelah wabah, orang-orang belum tenang. Ingatan duka dan derita belum berakhir selama wabah, bertambah dengan kabar-kabar krisis pangan global. Kita tetap mengaku “wajib” makan tapi pengertian-pengertian baru berdatangan setelah berurusan kekuasaan dan bisnis global.Berita-berita dan artikel-artikel para pakar menambahi beban hidup keseharian. Kita pantang mengeluh. Kita sadar nasib Indonesia dan dunia tapi memiliki batas-batas untuk menanggungkan derita. Makan selalu penting. Kita telanjur menekuni pelajaran makanan global ketimbang merenung seribuan hari tentang pangan lokal.Di buku berjudul
Berebut Makan: Politik Baru Pangan (2018) garapan Paul McMahon, kita mendapat peringatan tentang sengketa pangan abad XXI. Ketersediaan pangan untuk miliaran orang di dunia ditentukan lahan. Kita membaca peringatan:”Jika memang masih ada cadangan lahan tersedia, maka lahan itu berada dalam kawasan hutan, dan karena itu, tak boleh disentuh, sebab pembabatan hutan akan melepas lebih banyak gas-gas rumah kaca, menghancurkan keanekaragaman hayati terpenting dan mengubah pola curah hujan… Banyak orang sangat cemas atas lahan-lahan subur pertanian yang hilang setiap tahun akibat arus urbanisasi, industrialisasi, dan perusakan lingkungan”.Kita mengerti krisis pangan (global) sudah dicipta sejak lama, tak melulu gara-gara perang atau wabah. Kini, kita dipaksa merenung, berlanjut bingung dalam pilihan tindakan dan tebar pesan untuk umat manusia. Begitu. (*)
*) Penggiat literasi dan kuncen Bilik Literasi Solo
[caption id="attachment_290531" align="alignleft" width="150"]

Bandung Mawardi*)[/caption]
PADA masa lalu, krisis pangan biasa terjadi. Catatan-catatan sejarah bersumber masa kerajaan dan kolonial mengabarkan sulit pangan dan kelaparan terjadi di Nusantara. Ingatan-ingatan belum menghilang malah ditambahi dengan beragam berita dan artikel mengenai krisis pangan global. Konon, pemicu terbesar itu perang Rusia dan Ukraina.
Kita mengerti tapi membawa bingung-bingung sejak lama. Di Indonesia, krisis pangan terjadi tapi pidato atau jawaban penguasa dan kaum politik sering klise. Sekian catatan sejarah justru memunculkan kemahiran elite mengaburkan dan mengganti masalah-masalah dalam krisis pangan.
Krisis terjadi tapi ajaran-ajaran pangan tetap disampaikan para leluhur. Para pujangga menulis pelbagai cerita mengandung pesan-pesan pertanian dan adab makan. Urusan pangan mengikutkan persoalan-persoalan iman, politik, estetika, etika, perdagangan, dan lain-lain.
Kita mengutip dari
Serat Sanasunu gubahan Yasadipura II dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia: ”Janganlah menganggap ringan masalah makan sehingga tidak perlu dipikirkan… Masalah orang makan adalah masalah baku karena makan menjadi pengikat kehidupan”.
Di situ, pembaca tak mendapat pengisahan atau penjelasan beragam jenis pangan disantap orang-orang di Jawa dan diusahakan dalam pertanian.
Di buku berjudul
Ijtihad Progresif Yasadipura II dalam Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa (2004) susunan Sri Suhandjati Sukri, kita mendapat penjelasan:
”Mengingat pentingnya mengurangi makan bagi kewaspadaan batin di kalangan orang Jawa, masalah makan mendapat perhatian raja maupun pujangga, seperti tampak dalam
Serat Sanasunu dan
Wulangreh. Kekhawatiran atas terjadinya perubahan tata cara makan bagi orang Jawa karena pengaruh budaya Barat, mendorong Yasadipura II mengajarkan tata krama makan sebagaimana dilakukan Rasululullah”.
Kita tak sedang berpikiran krisis pangan. Serat itu mengingatkan tentang prihatin, tirakat, dan pemaknaan makan. Pada masa lalu, krisis pangan mungkin terjadi tapi orang sudah belajar menjadi sabar dengan mengurangi makan atau berpuasa. Kita mencomot penjelasan silam agar tak terlalu ketakutan bila diserbu berita-berita tentang krisis pangan global. Kita mungkin mula-mula menganggap itu terlalu politis dan bisnis.
Di
Kompas, 13 Oktober 2022, tajuk rencana mengenai pangan. Kita mengutip: ”Bertahun-tahun kita mendengungkan konsumsi pangan lokal, tetapi urusan ini tak pernah berujung pada satu aksi nyata dalam jangka panjang. kampanye pangan lokal masih sekadar menjadi slogan. Kini saatnya membuat ajakan memproduksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi riil. Keterpepetan karena krisis pangan yang ditandai dengan lonjakan harga pangan sudah selayaknya melecut semua pihak untuk melirik komoditas pangan setempat”.
Selama puluhan tahun, kita mendapat ”pelajaran” dan ”perintah” untuk menikmati makanan-makanan bukan lokal. Kita diajak menjadi konsumen global. Selera dibentuk dengan “indah”, “manis”, dan “baik”.
Jutaan orang menuruti selera sampai dalam pertaruhan harga (diri) dan “kebahagiaan”. Kita mungkin susah ingkar bila mulai kehilangan ilmu pangan dari para leluhur. Pengetahuan tentang pangan lokal pun jarang menjadi tema besar dalam pelajaran di sekolah dan percakapan-percakapan di ruang publik.
Sejak masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, sekian janji besar dan kebijakan sulit mewujudkan kedaulatan pangan (lokal). Pidato-pidato sudah disampaikan dengan menggebu dan kalem. Puluhan slogan dibuat untuk diucapkan bersama tanpa perjanjian terwujud. Kliping berita selalu mengingatkan bila pangan lokal itu kebablasan menjadi bualan kaum elite dan pemilik modal.
Pada hari-hari setelah wabah, orang-orang belum tenang. Ingatan duka dan derita belum berakhir selama wabah, bertambah dengan kabar-kabar krisis pangan global. Kita tetap mengaku “wajib” makan tapi pengertian-pengertian baru berdatangan setelah berurusan kekuasaan dan bisnis global.
Berita-berita dan artikel-artikel para pakar menambahi beban hidup keseharian. Kita pantang mengeluh. Kita sadar nasib Indonesia dan dunia tapi memiliki batas-batas untuk menanggungkan derita. Makan selalu penting. Kita telanjur menekuni pelajaran makanan global ketimbang merenung seribuan hari tentang pangan lokal.
Di buku berjudul
Berebut Makan: Politik Baru Pangan (2018) garapan Paul McMahon, kita mendapat peringatan tentang sengketa pangan abad XXI. Ketersediaan pangan untuk miliaran orang di dunia ditentukan lahan. Kita membaca peringatan:
”Jika memang masih ada cadangan lahan tersedia, maka lahan itu berada dalam kawasan hutan, dan karena itu, tak boleh disentuh, sebab pembabatan hutan akan melepas lebih banyak gas-gas rumah kaca, menghancurkan keanekaragaman hayati terpenting dan mengubah pola curah hujan… Banyak orang sangat cemas atas lahan-lahan subur pertanian yang hilang setiap tahun akibat arus urbanisasi, industrialisasi, dan perusakan lingkungan”.
Kita mengerti krisis pangan (global) sudah dicipta sejak lama, tak melulu gara-gara perang atau wabah. Kini, kita dipaksa merenung, berlanjut bingung dalam pilihan tindakan dan tebar pesan untuk umat manusia. Begitu. (*)
*) Penggiat literasi dan kuncen Bilik Literasi Solo





 Bandung Mawardi*)[/caption]
PADA masa lalu, krisis pangan biasa terjadi. Catatan-catatan sejarah bersumber masa kerajaan dan kolonial mengabarkan sulit pangan dan kelaparan terjadi di Nusantara. Ingatan-ingatan belum menghilang malah ditambahi dengan beragam berita dan artikel mengenai krisis pangan global. Konon, pemicu terbesar itu perang Rusia dan Ukraina.
Kita mengerti tapi membawa bingung-bingung sejak lama. Di Indonesia, krisis pangan terjadi tapi pidato atau jawaban penguasa dan kaum politik sering klise. Sekian catatan sejarah justru memunculkan kemahiran elite mengaburkan dan mengganti masalah-masalah dalam krisis pangan.
Krisis terjadi tapi ajaran-ajaran pangan tetap disampaikan para leluhur. Para pujangga menulis pelbagai cerita mengandung pesan-pesan pertanian dan adab makan. Urusan pangan mengikutkan persoalan-persoalan iman, politik, estetika, etika, perdagangan, dan lain-lain.
Kita mengutip dari Serat Sanasunu gubahan Yasadipura II dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia: ”Janganlah menganggap ringan masalah makan sehingga tidak perlu dipikirkan… Masalah orang makan adalah masalah baku karena makan menjadi pengikat kehidupan”.
Di situ, pembaca tak mendapat pengisahan atau penjelasan beragam jenis pangan disantap orang-orang di Jawa dan diusahakan dalam pertanian.
Di buku berjudul Ijtihad Progresif Yasadipura II dalam Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa (2004) susunan Sri Suhandjati Sukri, kita mendapat penjelasan:
”Mengingat pentingnya mengurangi makan bagi kewaspadaan batin di kalangan orang Jawa, masalah makan mendapat perhatian raja maupun pujangga, seperti tampak dalam Serat Sanasunu dan Wulangreh. Kekhawatiran atas terjadinya perubahan tata cara makan bagi orang Jawa karena pengaruh budaya Barat, mendorong Yasadipura II mengajarkan tata krama makan sebagaimana dilakukan Rasululullah”.
Kita tak sedang berpikiran krisis pangan. Serat itu mengingatkan tentang prihatin, tirakat, dan pemaknaan makan. Pada masa lalu, krisis pangan mungkin terjadi tapi orang sudah belajar menjadi sabar dengan mengurangi makan atau berpuasa. Kita mencomot penjelasan silam agar tak terlalu ketakutan bila diserbu berita-berita tentang krisis pangan global. Kita mungkin mula-mula menganggap itu terlalu politis dan bisnis.
Di Kompas, 13 Oktober 2022, tajuk rencana mengenai pangan. Kita mengutip: ”Bertahun-tahun kita mendengungkan konsumsi pangan lokal, tetapi urusan ini tak pernah berujung pada satu aksi nyata dalam jangka panjang. kampanye pangan lokal masih sekadar menjadi slogan. Kini saatnya membuat ajakan memproduksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi riil. Keterpepetan karena krisis pangan yang ditandai dengan lonjakan harga pangan sudah selayaknya melecut semua pihak untuk melirik komoditas pangan setempat”.
Selama puluhan tahun, kita mendapat ”pelajaran” dan ”perintah” untuk menikmati makanan-makanan bukan lokal. Kita diajak menjadi konsumen global. Selera dibentuk dengan “indah”, “manis”, dan “baik”.
Jutaan orang menuruti selera sampai dalam pertaruhan harga (diri) dan “kebahagiaan”. Kita mungkin susah ingkar bila mulai kehilangan ilmu pangan dari para leluhur. Pengetahuan tentang pangan lokal pun jarang menjadi tema besar dalam pelajaran di sekolah dan percakapan-percakapan di ruang publik.
Sejak masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, sekian janji besar dan kebijakan sulit mewujudkan kedaulatan pangan (lokal). Pidato-pidato sudah disampaikan dengan menggebu dan kalem. Puluhan slogan dibuat untuk diucapkan bersama tanpa perjanjian terwujud. Kliping berita selalu mengingatkan bila pangan lokal itu kebablasan menjadi bualan kaum elite dan pemilik modal.
Pada hari-hari setelah wabah, orang-orang belum tenang. Ingatan duka dan derita belum berakhir selama wabah, bertambah dengan kabar-kabar krisis pangan global. Kita tetap mengaku “wajib” makan tapi pengertian-pengertian baru berdatangan setelah berurusan kekuasaan dan bisnis global.
Berita-berita dan artikel-artikel para pakar menambahi beban hidup keseharian. Kita pantang mengeluh. Kita sadar nasib Indonesia dan dunia tapi memiliki batas-batas untuk menanggungkan derita. Makan selalu penting. Kita telanjur menekuni pelajaran makanan global ketimbang merenung seribuan hari tentang pangan lokal.
Di buku berjudul Berebut Makan: Politik Baru Pangan (2018) garapan Paul McMahon, kita mendapat peringatan tentang sengketa pangan abad XXI. Ketersediaan pangan untuk miliaran orang di dunia ditentukan lahan. Kita membaca peringatan:
”Jika memang masih ada cadangan lahan tersedia, maka lahan itu berada dalam kawasan hutan, dan karena itu, tak boleh disentuh, sebab pembabatan hutan akan melepas lebih banyak gas-gas rumah kaca, menghancurkan keanekaragaman hayati terpenting dan mengubah pola curah hujan… Banyak orang sangat cemas atas lahan-lahan subur pertanian yang hilang setiap tahun akibat arus urbanisasi, industrialisasi, dan perusakan lingkungan”.
Kita mengerti krisis pangan (global) sudah dicipta sejak lama, tak melulu gara-gara perang atau wabah. Kini, kita dipaksa merenung, berlanjut bingung dalam pilihan tindakan dan tebar pesan untuk umat manusia. Begitu. (*)
*) Penggiat literasi dan kuncen Bilik Literasi Solo
Bandung Mawardi*)[/caption]
PADA masa lalu, krisis pangan biasa terjadi. Catatan-catatan sejarah bersumber masa kerajaan dan kolonial mengabarkan sulit pangan dan kelaparan terjadi di Nusantara. Ingatan-ingatan belum menghilang malah ditambahi dengan beragam berita dan artikel mengenai krisis pangan global. Konon, pemicu terbesar itu perang Rusia dan Ukraina.
Kita mengerti tapi membawa bingung-bingung sejak lama. Di Indonesia, krisis pangan terjadi tapi pidato atau jawaban penguasa dan kaum politik sering klise. Sekian catatan sejarah justru memunculkan kemahiran elite mengaburkan dan mengganti masalah-masalah dalam krisis pangan.
Krisis terjadi tapi ajaran-ajaran pangan tetap disampaikan para leluhur. Para pujangga menulis pelbagai cerita mengandung pesan-pesan pertanian dan adab makan. Urusan pangan mengikutkan persoalan-persoalan iman, politik, estetika, etika, perdagangan, dan lain-lain.
Kita mengutip dari Serat Sanasunu gubahan Yasadipura II dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia: ”Janganlah menganggap ringan masalah makan sehingga tidak perlu dipikirkan… Masalah orang makan adalah masalah baku karena makan menjadi pengikat kehidupan”.
Di situ, pembaca tak mendapat pengisahan atau penjelasan beragam jenis pangan disantap orang-orang di Jawa dan diusahakan dalam pertanian.
Di buku berjudul Ijtihad Progresif Yasadipura II dalam Akulturasi Islam dengan Budaya Jawa (2004) susunan Sri Suhandjati Sukri, kita mendapat penjelasan:
”Mengingat pentingnya mengurangi makan bagi kewaspadaan batin di kalangan orang Jawa, masalah makan mendapat perhatian raja maupun pujangga, seperti tampak dalam Serat Sanasunu dan Wulangreh. Kekhawatiran atas terjadinya perubahan tata cara makan bagi orang Jawa karena pengaruh budaya Barat, mendorong Yasadipura II mengajarkan tata krama makan sebagaimana dilakukan Rasululullah”.
Kita tak sedang berpikiran krisis pangan. Serat itu mengingatkan tentang prihatin, tirakat, dan pemaknaan makan. Pada masa lalu, krisis pangan mungkin terjadi tapi orang sudah belajar menjadi sabar dengan mengurangi makan atau berpuasa. Kita mencomot penjelasan silam agar tak terlalu ketakutan bila diserbu berita-berita tentang krisis pangan global. Kita mungkin mula-mula menganggap itu terlalu politis dan bisnis.
Di Kompas, 13 Oktober 2022, tajuk rencana mengenai pangan. Kita mengutip: ”Bertahun-tahun kita mendengungkan konsumsi pangan lokal, tetapi urusan ini tak pernah berujung pada satu aksi nyata dalam jangka panjang. kampanye pangan lokal masih sekadar menjadi slogan. Kini saatnya membuat ajakan memproduksi dan mengonsumsi pangan lokal menjadi riil. Keterpepetan karena krisis pangan yang ditandai dengan lonjakan harga pangan sudah selayaknya melecut semua pihak untuk melirik komoditas pangan setempat”.
Selama puluhan tahun, kita mendapat ”pelajaran” dan ”perintah” untuk menikmati makanan-makanan bukan lokal. Kita diajak menjadi konsumen global. Selera dibentuk dengan “indah”, “manis”, dan “baik”.
Jutaan orang menuruti selera sampai dalam pertaruhan harga (diri) dan “kebahagiaan”. Kita mungkin susah ingkar bila mulai kehilangan ilmu pangan dari para leluhur. Pengetahuan tentang pangan lokal pun jarang menjadi tema besar dalam pelajaran di sekolah dan percakapan-percakapan di ruang publik.
Sejak masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto, sekian janji besar dan kebijakan sulit mewujudkan kedaulatan pangan (lokal). Pidato-pidato sudah disampaikan dengan menggebu dan kalem. Puluhan slogan dibuat untuk diucapkan bersama tanpa perjanjian terwujud. Kliping berita selalu mengingatkan bila pangan lokal itu kebablasan menjadi bualan kaum elite dan pemilik modal.
Pada hari-hari setelah wabah, orang-orang belum tenang. Ingatan duka dan derita belum berakhir selama wabah, bertambah dengan kabar-kabar krisis pangan global. Kita tetap mengaku “wajib” makan tapi pengertian-pengertian baru berdatangan setelah berurusan kekuasaan dan bisnis global.
Berita-berita dan artikel-artikel para pakar menambahi beban hidup keseharian. Kita pantang mengeluh. Kita sadar nasib Indonesia dan dunia tapi memiliki batas-batas untuk menanggungkan derita. Makan selalu penting. Kita telanjur menekuni pelajaran makanan global ketimbang merenung seribuan hari tentang pangan lokal.
Di buku berjudul Berebut Makan: Politik Baru Pangan (2018) garapan Paul McMahon, kita mendapat peringatan tentang sengketa pangan abad XXI. Ketersediaan pangan untuk miliaran orang di dunia ditentukan lahan. Kita membaca peringatan:
”Jika memang masih ada cadangan lahan tersedia, maka lahan itu berada dalam kawasan hutan, dan karena itu, tak boleh disentuh, sebab pembabatan hutan akan melepas lebih banyak gas-gas rumah kaca, menghancurkan keanekaragaman hayati terpenting dan mengubah pola curah hujan… Banyak orang sangat cemas atas lahan-lahan subur pertanian yang hilang setiap tahun akibat arus urbanisasi, industrialisasi, dan perusakan lingkungan”.
Kita mengerti krisis pangan (global) sudah dicipta sejak lama, tak melulu gara-gara perang atau wabah. Kini, kita dipaksa merenung, berlanjut bingung dalam pilihan tindakan dan tebar pesan untuk umat manusia. Begitu. (*)
*) Penggiat literasi dan kuncen Bilik Literasi Solo